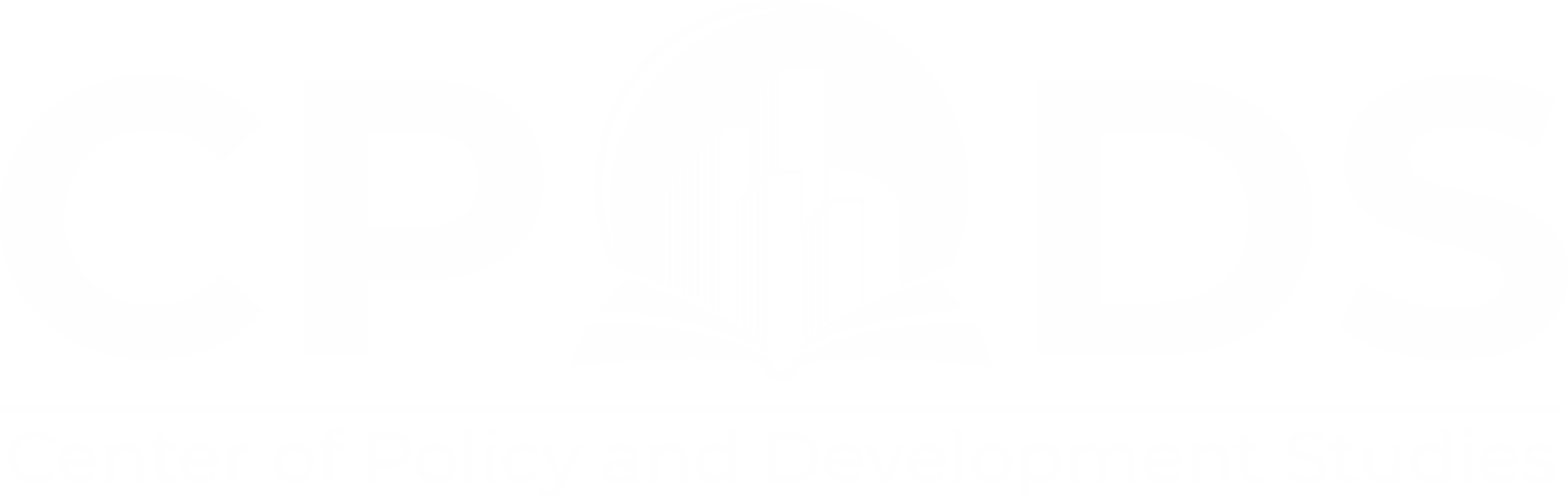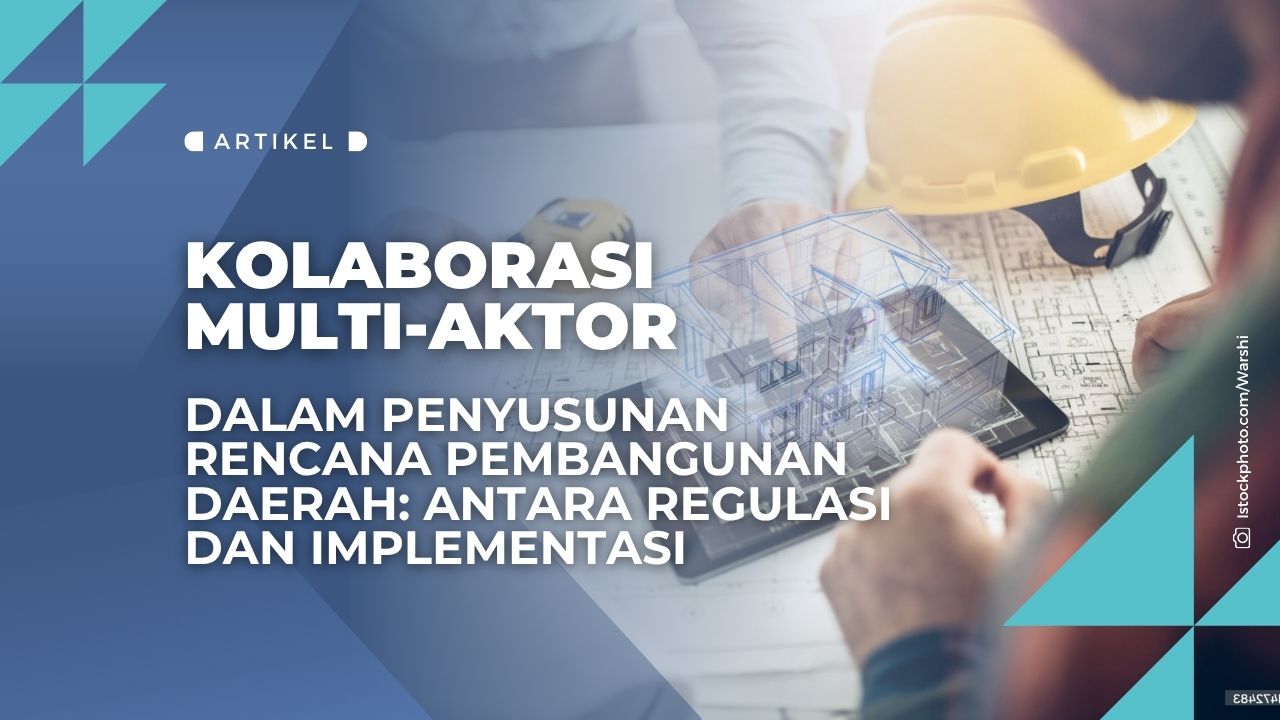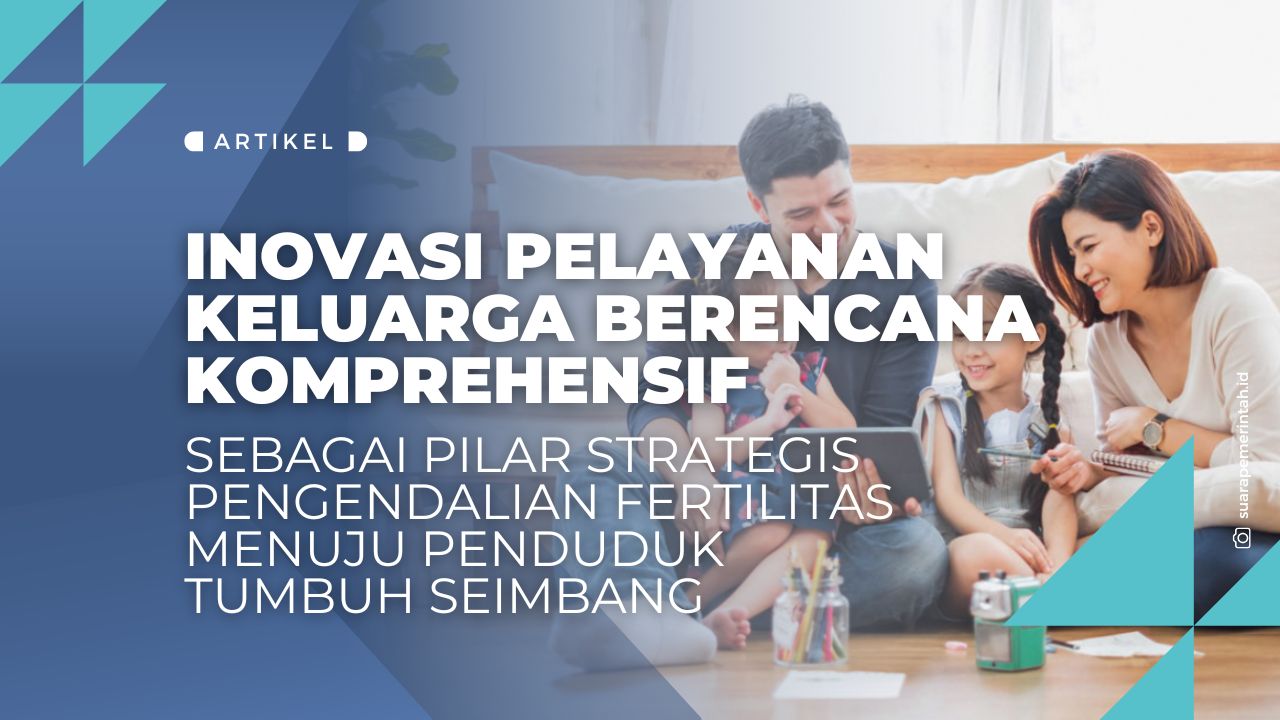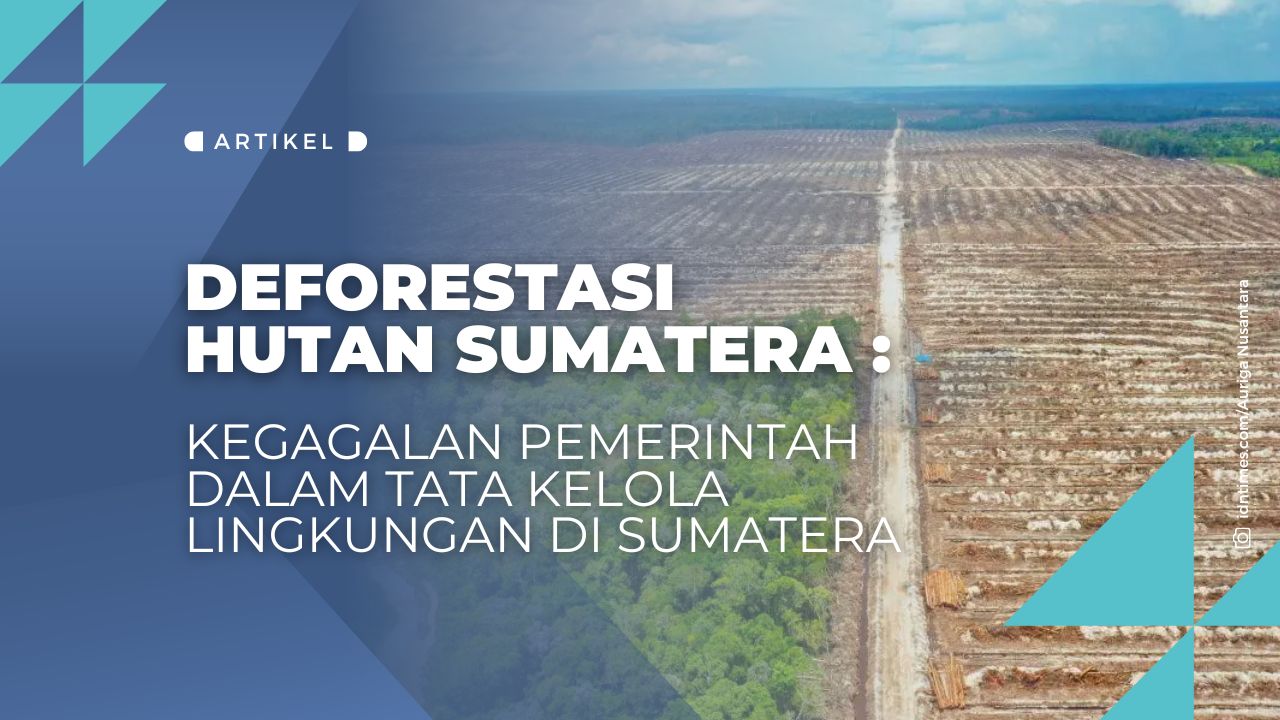Kolaborasi Multi-Aktor Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah: Antara Regulasi Dan Implementasi
Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari sistem desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah berupaya membangun sistem perencanaan yang partisipatif melalui kolaborasi antar-aktor, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Namun, meskipun secara regulatif prinsip kolaborasi telah diatur dengan jelas, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah wajib berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang menekankan pada keterlibatan multi-pihak.
Namun, data Bappenas (2023), menunjukkan bahwa hanya sekitar 42% pemerintah daerah yang melibatkan unsur non-pemerintah secara aktif dalam penyusunan dokumen RPJMD. Sisanya masih bersifat formalitas partisipasi publik hanya diwujudkan melalui forum Musrenbang tahunan yang belum berdampak signifikan terhadap prioritas kebijakan. Dari hasil evaluasi RPJMD 2019-2023 di 98 kabupaten/kota, lebih dari separuh rekomendasi Musrenbang masyarakat tidak masuk dalam dokumen akhir RPJMD karena dinilai “tidak sinkron dengan prioritas nasional” atau “di luar kewenangan daerah”.
Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Di tingkat normatif, semua mekanisme sudah tersedia. Tetapi dalam praktiknya, pemerintah daerah masih mendominasi proses perencanaan, sedangkan masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sering kali hanya dilibatkan di tahap konsultasi. Akibatnya, rencana pembangunan yang dihasilkan cenderung teknokratik dan tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan lokal.
Menurut teori governance kolaboratif (Ansell & Gash, 2007), kolaborasi yang efektif menuntut adanya trust building, komunikasi terbuka, dan komitmen jangka panjang antar-aktor. Pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai satu-satunya pembuat keputusan, tetapi harus menjadi fasilitator dan penghubung antar pemangku kepentingan. Dalam konteks pembangunan daerah, kolaborasi multi-aktor idealnya melibatkan:
- Pemerintah daerah (Bappeda, OPD, kelurahan/desa) sebagai koordinator;
- Masyarakat sipil dan kelompok lokal sebagai penyampai aspirasi dan kebutuhan;
- Akademisi dan perguruan tinggi sebagai penyedia analisis kebijakan dan data empiris;
- Sektor swasta dan dunia usaha sebagai mitra pendanaan dan inovasi;
- Media dan NGO sebagai pengawas publik dan penyebar informasi pembangunan.
Salah satu contoh penerapan kolaborasi yang relatif berhasil terdapat di Kota Surabaya. Pemerintah kota secara aktif melibatkan perguruan tinggi seperti ITS dan Universitas Airlangga dalam penyusunan Surabaya Smart City Masterplan. Proyek ini tidak hanya melibatkan birokrat, tetapi juga komunitas digital dan pelaku UMKM untuk menentukan prioritas inovasi berbasis kebutuhan warga. Hasilnya, pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Surabaya mencapai 75,12, lebih tinggi dari rata-rata nasional (69,5). Ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas-aktor dapat mendorong hasil pembangunan yang lebih konkret.
Sebaliknya, di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Malang atau Kabupaten Probolinggo, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih sangat rendah. Berdasarkan data BPS 2022, hanya 34% warga desa yang mengetahui proses Musrenbang, dan hanya 12% yang pernah terlibat langsung. Rendahnya literasi perencanaan ini membuat masyarakat sulit berperan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ego sektoral antar-OPD masih kuat; setiap dinas cenderung berfokus pada target kinerjanya sendiri tanpa melihat sinergi antar sektor. Akibatnya, rencana pembangunan menjadi terfragmentasi dan sulit dieksekusi secara integratif.
Dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang inovasi. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, konsep kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) dijadikan dasar pendekatan pembangunan nasional. Model ini kemudian diadaptasi oleh beberapa daerah, misalnya Kota Batu yang mengembangkan forum kolaboratif antara Dinas Pariwisata, pelaku UMKM, dan komunitas lokal dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal (2024–2029). Meski masih tahap awal, pendekatan ini memperlihatkan peningkatan efektivitas komunikasi antaraktor dan menghasilkan program prioritas yang lebih realistis.
Untuk memperkuat kolaborasi multi-aktor, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan:
- Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappeda sebagai koordinator lintas sektor dengan dukungan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi.
- Meningkatkan literasi perencanaan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan, agar partisipasi tidak sekadar formalitas.
- Mendorong transparansi data pembangunan, misalnya dengan membuka akses data RPJMD dan hasil Musrenbang secara daring.
- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan sektor swasta, baik dalam pengumpulan data, perumusan kebijakan, maupun pendanaan program.
- Menerapkan model evaluasi partisipatif, di mana masyarakat ikut memantau dan menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat bertransformasi dari pola top-down menjadi collaborative governance yang sejati. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, melainkan fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan demi tujuan pembangunan bersama.
Kolaborasi multi-aktor bukan sekadar jargon administratif, tetapi kebutuhan strategis untuk menghadapi kompleksitas pembangunan modern. Dalam era disrupsi digital dan perubahan iklim global, tantangan pembangunan semakin multidimensional, sehingga solusi tunggal dari pemerintah tidak lagi memadai. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, perencanaan pembangunan dapat menjadi adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Jika setiap daerah mampu menyeimbangkan antara regulasi yang partisipatif dan implementasi yang kolaboratif, maka tujuan utama desentralisasi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbasis potensi lokal bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan bersama.
Sumber data:
- Bappenas (2023). Evaluasi Partisipasi dalam RPJMD 2019–2023.
- BPS (2022). Indeks Pembangunan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017.
- UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014.
- Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.
Penulis: Durratun Nashihah, S.AP., M.AP. (Peneliti CPDS Indonesia)